BAMBANG SUGIHARTO Pengajar Filsafat di Unpar dan ITB, Bandung
Hal yang demikian dekat dengan kita sering kali justru jauh dari kesadaran. Layaknya ikan sulit menyadari dan memahami air, manusia modern pun harus melalui perjalanan panjang berputar untuk menyadari pentingnya lingkungan.
Manusia modern dan lingkungan alam memang senantiasa berada dalam tegangan: antara melepaskan diri darinya atau justru meleburkan diri ke dalamnya, antara titik berat pada kultur atau menjadi bagian dinamis dalam natur. Dunia seni adalah manifestasi menarik dari tegangan macam itu.
Di satu pihak manusia modern menyadari misteri, keunikan, dan pesona alam semesta umumnya melalui representasi artistiknya berupa lukisan, foto, musik, video ataupun film; di pihak lain kerangka artistik modern sendiri justru bertendensi kuat kian menghilangkan lingkungan alam sebagai bahan refleksinya (sebagai subject matter-nya). Ketika terlepas dari agama dan menjadi suatu wilayah otonom tersendiri dalam kiprah peradaban manusia, seni modern berangsur-angsur kian terlepas dari eksterioritas dan menyuruk kian mendalam ke wilayah interioritas, terperangkap dalam inflasi individu, dan memasuki wilayah skizofrenia yang ambigu dan kadang berbahaya.
Modernitas, estetika, dan alam
Sekurang-kurangnya sejak abad ke-17 hingga ke-18, dualisme Cartesian demikian kuat menguasai sikap manusia terhadap lingkungan alam. Alam adalah realitas wadag material, res extensa; sedangkan manusia, terutama akalnya, adalah realitas batin, pikiran-non-material, res-cogitans. Dualisme yang telah mengompori kinerja ilmiah awal ini lantas berselingkuh dengan kepentingan teknologi dan kapitalisme sehingga kian terlembagalah pola sikap Subyek-Obyek: manusia adalah subyek, alam adalah obyek belaka, medan untuk ditaklukkan, dieksplorasi, dan dieksploitasi. Maka, alam kehilangan pesona magisnya, kehidupan kehilangan misterinya. Pusat gravitasi adalah manusia dengan segala kepentingannya.
Di sisi lain, sikap epistemologis-teknis macam itu diimbangi oleh sikap estetis yang justru menghargai lingkungan alam. Memang tampak paradoks. Perspektif klasik estetika abad ke-18, yang menggumpal pada Immanuel Kant, meyakini bahwa yang pokok dalam apresiasi estetis adalah sikap ”tanpa kepentingan” (disinterestedness), yaitu sikap yang melepaskan diri dari kepentingan sehari-hari yang teknis dan praktis atau pun kepentingan pribadi. Lingkungan, baik urban, rural maupun belantara hutan, dilihat sebagai sesuatu yang sublim dan indah. Namun, di sini lingkungan alam sebenarnya tetaplah juga diapresiasi secara formalistik sebagai medan obyek, dan terutama sebagai lanskap, yang berkarakter picturesque. Pada abad lalu memang ada juga orang seperti JJ Rousseau yang melihat lebih jauh, yakni melihat alam sebagai setting kodrat manusia yang lebih otentik ketimbang setting kultural iptek modern, yang dianggapnya meracuni potensi-potensi natural manusia. Namun, pandangan macam ini baru menemukan gaungnya yang tepat kelak di abad ke-19 pada masa Romantik.
Romantisisme abad ke-19 memang jatuh cinta pada alam. Henry David Thoreau atau juga John Muir, misalnya, dengan cara yang berbeda menekankan pentingnya interaksi dengan alam liar. Alam liar bagi mereka lebih tinggi daripada peradaban dan kultur manusia. Interaksi noneksploitatif dengan alam itu akan membawa transformasi penting bagi dunia manusia. Darwin bahkan mendudukkan manusia sekadar sebagai salah satu unsur saja dalam alam. Sementara alam sudah dilihatnya sebagai berbagai unsur yang saling tergantung satu sama lain. Di sisi lain para pengkritik budaya modern teknologis macam Herder, Goethe, Humboldt ataupun Schiller kendati cenderung menganggap modernitas sebagai dangkal dan nonreflektif, toh tetap juga memberi prioritas lebih pada kultur ketimbang natur, pada seni ketimbang teknologi. Seperti halnya Hegel, yang dalam sistem filsafatnya juga tetap memprioritaskan realitas artifaktual sebagai antitesis atas realitas natural. Tapi, pada Nietzsche agak lain. Dalam kerangka berpikirnya kultur, seni, dan natur bukanlah hal-hal bertentangan. Ketika dikritiknya bahwa peradaban modern (Zivilisation) adalah proses de-naturalisasi insting dan de-intellektualisasi kultur, maka bagi Nietzsche kultur yang sebenarnya haruslah merupakan manifestasi dari insting natural daya-daya hidup, dan itu pula kekuatan yang mesti diungkapkan seni. Kendati semua itu secara umum pola apresiasi terhadap alam dalam karya seni tetaplah: subyek terhadap obyek artifaktual seni. Artinya, alam tampil dalam representasi artistiknya.
Di penghujung abad ke-19 tendensi ambivalen macam di atas itu mulai menghilang dalam style baru yang muncul saat itu: ”impresionisme”. Sebabnya karena alam sendiri sebagai obyek mulai menyublim di sana. Munculnya kamera foto saat itu mengakibatkan pola ”mimetis” dan konsep ”representasi” dalam kiprah seni menjadi problematis. Maka, para seniman lantas asyik mempersoalkan misteri ”persepsi” itu sendiri. Timbullah gagasan bahwa melukis, misalnya, bukan berarti menangkap realitas wujud dalam arti harfiah fisiknya, melainkan menangkap kesan sesaat: menangkap cuaca, cahaya, kabut, udara, kontur imaji total dalam momen-momen yang berlari, kesemantaraan yang tidak abadi. Ada pergeseran titik berat di sana: dari visualitas ke impresi jiwa; dari benda ke suasana.
Pergeseran dari eksterioritas ke interioritas ini makin radikal dalam ”ekspresionisme” yang masuk lebih ke dalam, memberi tekanan berat pada reaksi mental, emosi, gelegak energi si seniman pribadi. Maka, atas nama ekspresi, obyek pun didistorsi sesuka senimannya. Kalaupun alam menjadi obyeknya, bukan alam itu sendiri yang penting, melainkan disposisi mental sang seniman (Van Gogh, dan sebagainya), atau upaya untuk mengundang reaksi emosi dan rasa dari sang pemirsa (Matisse, Derain, dan sebagainya). Dan tendensi ini kian mengkristal dalam ”abstraksionisme”. Di sana aspek representasi obyek di luar hilang sama sekali. Yang terjadi lantas hanyalah eksplorasi ruang batin pada tingkatnya yang paling sublim, gelap, dan misterius yang tak terpikirkan sekaligus tak terelakkan (Kandinsky, Rothko, Pollock, dan sebagainya).
Ironisnya, di sisi lain abstraksionisme adalah juga renungan atas elemen-elemen dasar bentuk, rupa, dan materialitas itu sendiri juga (Malevich, Mondrian, Kurt Schwitters, dan lain-lain). Maka, yang terjadi di sini sebenarnya adalah proses interiorisasi subyek sekaligus penyelaman ke balik obyek. Kalaupun masih ada jejak-jejak obyek luaran di sana, itu muncul dalam bentuk reduksinya ke dalam elemen-elemen dasarnya belaka.
Di abad ke-20, sejak pasca-Perang Dunia I dan II, Dadaisme, dan revolusi kaum muda tahun 1960-an terjadi perubahan mendasar ihwal hubungan antara seni dan lingkungan di luarnya. Dari sudut bentuk terjadi eksplorasi segala kemungkinan baru, yang bahkan menerabas segala batasan kategorial modern. Ini khususnya terasa intens dalam tendensi Avantgardisme. Lukisan dua dimensi dibongkar, berubah menjadi ”kolase”; kolase menjadi ”asemblase” tiga dimensi; asemblase tumpah ke luar bidang kanvas dan tergerai di lantai menjadi ”instalasi”; instalasi menjelma menjadi gerak dalam ”performance-art” atau happening. Di awal abad ke-21 performance-art akhirnya ke luar dari ruang eksklusifnya menjadi aksi sosial dalam segala banalitas konteksnya. Yang terjadi di sini adalah lenyapnya batas angker antara dunia seni yang eksklusif dan situasi sehari-hari. Pola apresiasi seni pun berubah total bukan lagi sekadar Subyek terhadap Obyek, melainkan Subyek terhadap Setting. Seni menjadi peristiwa kolektif dalam setting multisensoris totalnya.
Permasalahannya
Ketika seni menyatu kembali dengan denyut kehidupan sehari-hari, tentu peluang bagi seni untuk mencebur kembali dengan alam pun besar. Masalahnya adalah bahwa sejak impresionisme hingga berbagai bentuk avantgardisnya, seni modern telanjur demikian kuat terperangkap dalam kerangka interioritas dunia manusia. Seni mengalami ”inflasi individu” sedemikian hingga terasa narsistik. Ia menjadi semacam petualangan ke dalam lapisan-lapisan psike paling tersembunyi dalam diri, wilayah gelap yang paling tabu, tak terduga dan liar (Rudolf Schwarzkogler yang menyayati kemaluannya hingga mati, misalnya, atau Vito Acconci yang merekam dirinya bermasturbasi). Ia bermain dengan ambang batas daya toleransi kejiwaan dan kebertubuhan (Stelarc yang menggantung tubuhnya dengan kail-kail besar, misalnya), serta mengeksplorasi wilayah insting-insting paling purba, ganas, dan keras.
Konsekuensi dari ini semua adalah makin lenyapnya alam dalam karya seni dan sekaligus makin besar tendensi skizofrenia alias kegila-gilaan di sana. Karya seni bukan hanya mengeksplorasi wilayah kegilaan, melainkan sendirinya juga berkarakter skizofrenik. Tengoklah karya-karya macam body-art dari Chris Burden (yang menembak dirinya sendiri), atau performance-art dari Carolee Schneeman (yang memasuk-keluarkan benda tertentu ke dalam vaginanya), teater Artaudian yang mengeksplorasi impuls-impuls tubuh dan emosi paling liar, atau film-film Peter Greenaway dan Jarman yang persis memainkan ambiguitas pengalaman-pengalaman liminal tubuh, emosi, dan imajinasi. Tak mengherankan bahwa akhirnya dunia seni macam ini melahirkan pula seni-mayat seperti yang dipamerkan seniman ahli bedah Günther von Hagens, yang karya seninya berupa 200-an mayat yang telah diplastinasi menjadi berbagai patung tubuh. Semua gejala ini akhirnya juga memaksa para apresiator awam memasuki ambang-batas daya tahan psikenya sendiri juga.
Yang terjadi di sini lantas bukan hanya seni kehilangan dimensi transendensi, melainkan bahwa ia tenggelam dalam medan imanensi: imanensi dunia manusia, tetapi juga imanensi dunia seni yang eksklusif itu sendiri. Seni terus-menerus memperkarakan dirinya sendiri saja, lantas menjadi begitu akrab bukan saja dengan naluri kegilaan, melainkan juga dengan naluri-naluri kematian. Bukan hanya para senimannya menyiksa diri sampai mati atau mengeksplorasi kematian, setiap aliran pun saling mencurigai bahkan saling bantai. Yang muncul, khususnya dalam Avantgardisme, akhirnya hanyalah sensasi demi sensasi, tanpa isi. Tidaklah mengherankan bahwa seni modern sendiri pun akhirnya ”mati” (kata Arthur Danto).
Dalam seni modern memang kategori ”keindahan” tak lagi dipedulikan, diganti ”kebermaknaan”, ”kebenaran” (kebenaran eksistensial) ataupun sensasi permukaan (the erotics , kata Susan Sontag). Dan memang sulit sekali mengapresiasi keindahan dalam karya-karya modern yang kadang demikian brutal itu. Tentu saja fokus kuat pada kebenaran eksistensial ini bukan tanpa nilai. Ia telah membawa seni memasuki medan reflektivitas manusia ke tema-tema dan kedalaman paling tersembunyi dan paling tak terduga, yang dalam karya-karya besar klasik tak pernah dieksplorasi dan diolah secara demikian eksplisit.
Dan fokus terhadap kebenaran eksistensial itu pula yang akhirnya telah membawa seni melebur kembali dalam banalitas hidup sehari-hari yang pantas disyukuri. Sayangnya, ketika ia telah menyatu dengan kehidupan sehari-hari ia cenderung menjadi gerakan-gerakan sosial biasa. Pada titik ini ia pun terancam kehilangan kekuatan craftsmanship-nya, dan dengan itu kehilangan pula daya magis-metaforiknya, lantas jatuh menjadi sekadar aktivisme yang kelewat harfiah belaka. Singkatnya, permasalahan seni modern terletak pada narsisismenya yang cenderung skizofrenik, keterkungkungannya pada imanensi yang akhirnya sering jatuh menjadi sekadar rangkaian sensasi, hilangnya sisi ”keindahan” dan lemahnya kekuatan metaforis-magis.
Aspek keindahan dan kekuatan metaforik mestinya tetaplah penting dalam seni. Hanya saja, keindahan barangkali kini perlu juga dipahami secara lebih luas. Bukan sekadar keindahan kompositoris atau picturesque bentuk visual, tetapi terutama keindahan dalam arti kemampuan suatu gubahan olah-bentuk untuk menyentuh lapisan batin paling dalam dan efektif dalam membuka kesadaran. Keindahan penting karena ia adalah cara paling efektif dimensi transendensi menyentuh indra batin kita; sekaligus cara manusia keluar dari keterpenjaraan intern-nya dan menyatu dengan Ruh Semesta, dengan Anima Mundi, dengan dunia batin alam yang lebih luas. Sedang metafor penting karena ia merangsang proses transformasi kesadaran ke tingkat lebih tinggi, proses de-literalisasi kenyataan sehari-hari, yang memungkinkan kita melihat hal yang lebih jauh dan lebih besar di balik hal-hal fisik yang tampak sepele. Bila keindahan dan kekuatan metaforik tetap diperhitungkan dalam praktik berkesenian, maka lebih mudah agaknya seni menggamit kembali realitas di luarnya: lingkungan semesta, bahkan keilahian kosmik transendental.
Kiblat baru berkesenian
Ketika periode avantgard modern berlalu, dalam kiprah seni kontemporer pascamodernisme hari ini sebenarnya kepedulian terhadap alam memang makin besar. Alam digunakan sebagai bagian integral dari patung, tarian, teater, ataupun instalasi, dan menjadi inspirasi utama pula dalam berbagai bentuk kerja desain. Sepertinya seniman mutakhir saat ini tak lagi sedemikian terkungkung oleh individualitasnya. Sosok karya seni pun bukan lagi semata berupa entitas artifaktual mandiri, melainkan sering pula berupa proses dan interaksi. Nilai karya seni Christo yang umumnya berupa instalasi-instalasi raksasa dalam setting alam, misalnya (layar raksasa yang membentangi perbukitan atau membingkai pulau-pulau), terletak bukan saja pada nilai kekaryaan monumental dari seorang seniman bernama Christo, melainkan juga pada daya gugah puitiknya bagi kesadaran pemirsa terhadap alam, sekaligus pada seluruh proses kerja Christo yang melibatkan demikian banyak pihak dan tahapan proses birokrasi. Totalitas proses dan interaksi macam itu pula yang menandai kebermaknaan proyek-proyek teater-lingkungan dari seniman macam Richard Schechner, proyek tarian Sardono W Kusumo, aksi tanam pohon Tisna Sanjaya, kiprah Arahmaiani di desa-desa di Jawa Tengah, atau bahkan dalam pembuatan film-film Garin Nugroho, misalnya. Dan berkat makin gencarnya gerakan environmentalisme, kiprah kesenian pun makin banyak menggarap tema dan perspektif lingkungan.
Namun, dalam kaitan dengan lingkungan, barangkali yang lebih radikal menentukan keterkaitan antara seni dan lingkungan sebenarnya adalah imajinasi metafisik di balik konsep ”seni” dan ”berkesenian” itu sendiri. Selagi seni tetap dimengerti sebagai reflektivitas dan virtuositas individual seperti dibayangkan dalam kerangka estetika Aufklärung Kantian, maka seni akan tetap urusan para genius yang langka, suatu kemewahan elitis, yang hanya pantas dipandangi di etalase galeri, museum ataupun panggung-panggung kesenian bergengsi, tanpa sungguh-sungguh bisa diapresiasi dan dipahami kebanyakan orang, tanpa relevansi dengan kehidupan sehari-hari.
Pada titik ini pandangan metafisik tradisional pramodern tentang kesenian justru menjadi sangat menarik dan relevan. Seperti masih banyak kita saksikan di daerah-daerah, macam di Bali, Toraja, ataupun Asmat, seni bukanlah semata-mata perkara teknis, skill, dan virtuositas karenanya bukanlah hanya urusan para genius. Seni bukan pula soal perspektif disinterested berjarak, melainkan justru sebaliknya, soal keterlibatan total dalam lingkungan, yang dasarnya adalah imajinasi metafisik yang berkarakter monistik: bahwa manusia adalah bagian dari totalitas kenyataan kehidupan yang satu jua; bahwa segenap realitas adalah totalitas yang berjiwa.
Di sini seni lantas adalah perayaan hubungan ruhani kosmik itu, adalah aktivitas-aktivitas olah-bentuk dalam rangka memberi dimensi batin pada benda-benda dan peristiwa. Dalam kerangka macam ini, seni lantas adalah urusan semua orang. Seni bukan pertama-tama soal kepiawaian, melainkan soal ritual dan perayaan. Kecanggihan teknis bernilai dalam rangka intensifikasi perayaan itu. Dalam perspektif ini bukan para seniman yang merupakan manusia istimewa, melainkan setiap manusia adalah seniman istimewa. Yang dianggap karya seni pun bukan lagi sekadar obyek artifaktual tertentu, melainkan keseluruhan proses dan interaksi yang terjadi, keseluruhan unsur dan peristiwa. Seni bukan pula ekspresi pribadi yang idiocyncratic, melainkan proses artikulasi diri-komunal, yang setiap kali mendefinisikan ulang hakikat kesatuan dasariah antara manusia dan alam, realitas mikro dan realitas makro; proses me-recharge ruh individu maupun kolektif dengan menyatukannya setiap kali dengan Anima Mundi. Kesenian adalah aneka ritual yang setiap kali mengingatkan kembali misteri, kerumitan, keagungan, dan keindahan daya-daya kosmik transendental. Maka, di sini kepekaan estetik adalah sekaligus kepekaan terhadap yang sakral.
Maka, agaknya seni akan bisa lebih total menggamit kembali lingkungan alam kini hanya bila seni kontemporer dapat bersekutu kembali dengan khazanah dan worldview metafisik tradisional macam itu. Berbagai gejala ke arah sana telah muncul di mana-mana, entah dalam rupa ritualisme baru, performance art sebagai gerakan sosial atau pun berbagai eksperimen yang menyenyawakan ruh tradisional dengan seni kontemporer. Dan di sana yang menjadi kunci akhirnya adalah bahwa krisis ekologis fisik sebenarnya berakar pada masalah krisis spiritual. Bukanlah kebetulan bahwa ketika seni modern terlepas dari medan spiritual, ia menjadi teramat akrab dengan naluri-naluri kematian, penghancuran, dan kegilaan. Namun, di sisi lain ini tak mesti berarti bahwa lantas seni mesti dikait-kaitkan dengan agama.
Medan spiritual jauh lebih luas dan lebih misterius ketimbang yang sempat diartikulasikan oleh agama. Bahkan pada titik tertentu agama sebagai pelembagaan spiritualitas bisa justru mematikan dinamika spiritual yang otentik dan membunuh seni juga , atas nama legalisme formal, ritualisme, dogmatisme, dsb. Yang lebih dibutuhkan adalah bagaimana seni mampu di satu pihak mengartikulasikan gejolak batin kolektif yang otentik, di pihak lain sekaligus menghadirkan dimensi transendensi ke dalam realitas sehari-hari. Demikian transendensi, keindahan dan kekuatan metaforis agaknya bukanlah hal yang kedaluwarsa. Sebaliknya, itu tetaplah unsur-unsur esensial yang menjaga kebermaknaan dan kesehatan kesenian dan dunia manusia.
11/14/2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


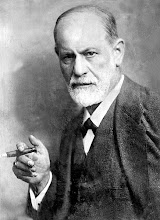




No comments:
Post a Comment